---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |
| MI/Liliek Dharmawan |
KABUT tebal menyelimuti pepohonan rindang di sepanjang jalanan berliku. Sesekali sejumlah warga berjalan menembus kabut pagi itu.
Ketika memasuki wilayah wisata Gunung Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pemandangan berubah. Terlihat tanah datar dan candi-candi peninggalan kejayaan Dinasti Sanjaya pada ketinggian 2.093 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Tempat itu sangat pas untuk menyatu dengan alam. Itulah mengapa kemudian daerah itu disebut Dieng, yang berasal dari kata di yang berarti gunung dan hyang yang berarti kahyangan.
Pemandangan semacam itu bukanlah kondisi kekinian. Cerita Dieng dengan keanekaragaman hayati yang begitu kaya tinggal kenangan. Sejak 30 tahun silam, kondisinya benar-benar berubah. Sepanjang mata memandang di perjalanan menuju Dieng ialah hamparan perkebunan, apalagi kalau bukan perkebunan kentang yang telah menjadi primadona warga Dieng sejak era 1980-an. Bau sedap pepohonan hutan kini tergantikan oleh semerbak pestisida dan pupuk kandang sebagai bagian tak terpisahkan dari Dieng.
Ubi bulat sebesar bola tenis itu telah mengubah segalanya. Begitu dikenalkan kepada warga Dieng, keberhasilan memang sangat terasa.
Bagaimana tidak, sebagian warga sebelumnya menjadi petani hutan dengan mencari kayu bakar dan penghasilan mereka hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun hal itu tiba-tiba berubah seketika.
Dengan lahan sekitar 1 hektare (ha), ketika itu mereka mampu menghasilkan panenan kentang senilai Rp30 juta hingga Rp40 juta.
''Waktu itu, tiap kali panen, saya bisa membeli pakaian baru, sabuk, celana, hingga sepatu baru dengan harga yang cukup mahal. Istilahnya 300-an,'' tutur Paudin, petani kentang di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
Artinya, dari ujung kaki hingga atas menggunakan barang seharga sekitar Rp300 ribu. Seperti sepatu yang harganya Rp300 ribu, celana Rp300 ribu, dan baju atasan juga Rp300 ribu.
Masyarakat pegunungan Dieng, kata Paudin, sejak lama memang penggemar fesyen. Tiap kali usai panen kentang, warga daerah itu langsung berburu pakaian ke Kota Wonosobo. Bahkan, ada pula yang sampai memburu pakaian ke luar kota, seperti Yogyakarta dan Semarang.
''Pokoknya waktu itu puas sekali beli pakaian tiap panen. Orang sini tidak terlalu tertarik membeli barang elektronik, seperti kulkas dan lainnya. Tapi kalau pakaian, pasti dibeli tiap panen. Jadi belinya tiap akan Lebaran dan panen,'' kata dia.
Longsor
Pegunungan Dieng kini terlihat tandus. Hutan di sana sudah dibabat habis demi tanaman kentang. Padahal hutan Dieng diperuntukkan sebagai kantong-kantong cadangan air.
Bila musim penghujan tiba, yang terjadi adalah tanah longsor di mana-mana. Korbannya pun tidak sedikit.
Wakil Bupati Wonosobo Maya Rosida, beberapa waktu lalu, menjelaskan, bila lingkungan Wonosobo rusak, akan berpengaruh pada 17 kabupaten yang ada di sekitarnya. ''Karena posisi Wonosobo sangat strategis.''
Penggundulan hutan memang sudah terjadi sangat lama.
Kisah serupa juga dialami Kabupaten Banjarnegara, Jateng. Menurut Haryanto Agus, dari Bappeda Kabupaten Banjarnegara, sudah 20% hutan di Pegunungan Dieng dibabat dan digantikan dengan tanaman kentang.
''Petani kentang merupakan petani egois. Mereka tidak mau tanaman tertutup pohon apa pun karena takut busuk atau mati. Makanya semua pohon tidak boleh ada di sekitar tanaman kentang,'' terang Haryanto.
Bisa dibayangkan Pegunungan Dieng yang dulunya sangat subur dan hijau kini menjadi gundul karena dipenuhi perkebunan kentang.
Dia menyebutkan penggundulan hutan di dataran tinggi Dieng berimbas pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mrica.
Setiap kali hujan, air yang mengalir melalui Sungai Tulis yang kemudian masuk ke Bendungan Mrica bercampur dengan lumpur. Bahkan, sudah ada empat desa tidak jauh dari PLTA Mrica yang hilang karena sering kebanjiran. ''Ya penghuninya pindah semua karena sudah langganan banjir. Desa-desa itu hanya tinggal kenangan,'' kata Haryanto.
Tugiman, Kepala SDN Kasinoman 2 Kabupaten Banjarnegara, menggambarkan, ketika banjir tiba, air yang mengalir dari Dieng menuju Sungai Tulis berupa lumpur.
''Setiap banjir mengerikan bagi penduduk di bawah karena lumpurnya lebih banyak. Ini akibat di atas sudah tidak ada lagi hutan. Tanaman kentang membuat daerah di pegunungan rawan longsor dan terbuang melalui sungai,'' jelas Tugiman.
Pada musim hujan sedikitnya ada sekitar 4,5 juta ton lumpur yang terbawa dari Dieng ke Waduk Mrica.
Waduk yang airnya dimanfaatkan untuk pasokan listrik Jawa-Bali itu meluap dipenuhi lumpur. Hal itu menghambat pengoperasian PLTA Mrica karena waduk dipenuhi endapan lumpur. Untuk mengeruk lumpur tidaklah mudah karena biayanya cukup tinggi.
''Kami pun selalu memantau perkembangan di atas (Dieng). Pendekatan terus dilakukan agar tidak terjadi penggerusan hutan terus-menerus,'' tambah Haryanto.
Kabag Humas Pemkab Wonosobo Agus Wibowo meminta petani kentang tidak salah paham terhadap niat pemerintah daerah mengonservasi lahan di Dieng.
''Kalau bicara kerusakan Dieng itu bukan kami menuduh petani. Namun ada berbagai faktor, seperti pola tanam yang tidak sesuai, eksploitasi lahan, di samping kondisi tanah di Dieng yang memang sudah labil.''
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baca Juga:




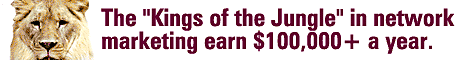





Tidak ada komentar:
Posting Komentar